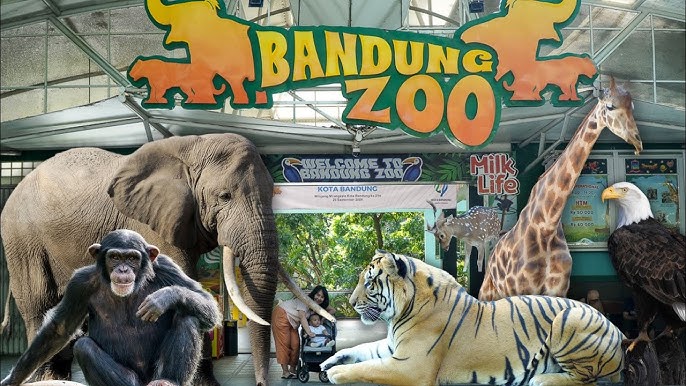JAKARTA - Ketahanan sektor kesehatan nasional kini berada di persimpangan jalan. Di tengah upaya pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi, industri alat kesehatan (alkes) lokal justru menghadapi tantangan serius yang mengancam keberlanjutan ekosistemnya. Dari persoalan sistem pengadaan hingga tekanan geopolitik global, sederet faktor ini membentuk kondisi yang tidak ideal bagi pertumbuhan sektor strategis ini.
Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (Hipelki) mengangkat kekhawatiran mengenai potensi stagnasi dalam pengembangan alkes nasional. Dalam forum internal organisasi, Ketua Umum Hipelki, Randy H. Teguh, mengungkapkan betapa besar hambatan yang dihadapi pelaku industri di berbagai lini rantai pasok mulai dari produsen, distributor, hingga laboratorium pendukung.
Menurut Randy, meskipun Hipelki terus berupaya menjadi penggerak utama pembangunan ekosistem alat kesehatan nasional, realitas di lapangan tidak sejalan dengan harapan. “Kita masih memiliki banyak kekurangan di dalam pembangunan ekosistem alkes karena ekosistem hilir, produsen dan distributor, mengalami berbagai guncangan,” ujarnya.
- Baca Juga Isak Jadi Pilar Baru Liverpool
Situasi ini diperparah oleh beban geopolitik dan tekanan ekonomi global. Dalam pandangan Randy, pemerintah tengah berada di tengah pusaran pilihan-pilihan sulit yang harus diambil. Di satu sisi, terdapat ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, namun di sisi lain, ketahanan kesehatan nasional menuntut perhatian serius.
Ia menyebut, pemerintah sering kali terdesak untuk menentukan prioritas, terutama ketika harus menyikapi badai ekonomi dan gejolak geopolitik. Kondisi ini membuat sumber daya dan energi negara terkuras ke berbagai sektor, menyisakan sedikit ruang untuk pembangunan ketahanan kesehatan secara menyeluruh.
“Sehingga hampir tidak ada yang tersisa untuk difokuskan kepada pembangunan ketahanan kesehatan, meskipun kegiatan layanan kesehatan rutin seperti pemeriksaan kesehatan gratis masih tetap mendapatkan prioritas,” ungkap Randy.
Lebih jauh, Randy mengungkapkan tiga masalah pokok yang menghambat pertumbuhan industri alkes. Pertama adalah sistem pengadaan terpusat yang dianggap kurang memberi ruang bagi distributor di daerah untuk terlibat aktif. Sistem ini mengkonsentrasikan keputusan di satu titik, sehingga peluang bagi pelaku usaha lokal menjadi sangat terbatas.
Kedua, tekanan harga yang diberlakukan terhadap alkes membuat produsen dan distributor tidak memiliki margin keuntungan yang memadai. Akibatnya, pelaku industri kesulitan mengadopsi teknologi baru karena keterbatasan dana untuk investasi inovasi.
Masalah ketiga yang tak kalah pelik adalah sistem pembayaran yang berlarut-larut. Banyak distributor disebut mengalami kesulitan likuiditas karena belum menerima pembayaran dari rumah sakit atas produk yang telah disalurkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pihak rumah sakit perlu melewati proses audit terlebih dahulu sebelum dapat melunasi kewajiban mereka.
“Akibatnya, distributor kehabisan modal dan tidak dapat membayar atau membeli dari produsen. Tentu saja hal ini menyebabkan tersendatnya pergerakan rantai pasok alkes dan pada akhirnya menyebabkan matinya seluruh ekosistem alkes,” jelas Randy.
Ketidakseimbangan ini, menurutnya, menyebabkan efek domino yang berdampak pada sektor-sektor lainnya dalam ekosistem. Di sisi hulu, peneliti tidak mendapatkan insentif yang layak untuk melanjutkan pengembangan teknologi alkes. Sementara produsen komponen dan bahan baku menghadapi kesulitan dalam mencapai kelayakan ekonomi untuk tetap berproduksi.
Bahkan, laboratorium yang menjadi bagian dari ekosistem pendukung juga tidak mendapatkan rangsangan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas layanan mereka. Di sisi lain, minat investor untuk masuk ke industri alkes nasional pun menurun drastis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Situasi ini, lanjut Randy, sangat mengkhawatirkan karena menyangkut lebih dari sekadar urusan dagang. Ia menegaskan bahwa jika pembangunan ekosistem alkes gagal, dampaknya akan lebih luas daripada sekadar melemahnya sektor kesehatan. Dampaknya bisa menyentuh aspek strategis lain seperti upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perlu kita ingat bahwa kegagalan pembangunan ekosistem alkes tidak hanya berpengaruh kepada ketahanan kesehatan, tetapi juga kepada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah,” tegas Randy.
Dalam konteks ini, kehadiran perjanjian dagang yang memungkinkan masuknya alkes impor dalam jumlah besar juga menjadi perhatian tersendiri. Para pelaku industri dalam negeri mencemaskan bahwa gelombang masuknya produk alkes dari luar negeri dapat semakin memperlemah posisi produsen lokal yang sejak awal sudah dalam kondisi kritis.
Randy menilai bahwa permasalahan yang terjadi saat ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut arah kebijakan dan komitmen jangka panjang dalam membangun kemandirian sektor kesehatan nasional. Tanpa adanya keberpihakan terhadap industri alkes lokal, ia khawatir Indonesia akan terus berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi tantangan kesehatan global.
Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan dorongan kebijakan yang terukur agar industri alkes tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan mandiri. Jika tidak, ketergantungan terhadap alkes impor akan terus berlanjut dan memperburuk posisi Indonesia dalam krisis kesehatan mendatang.