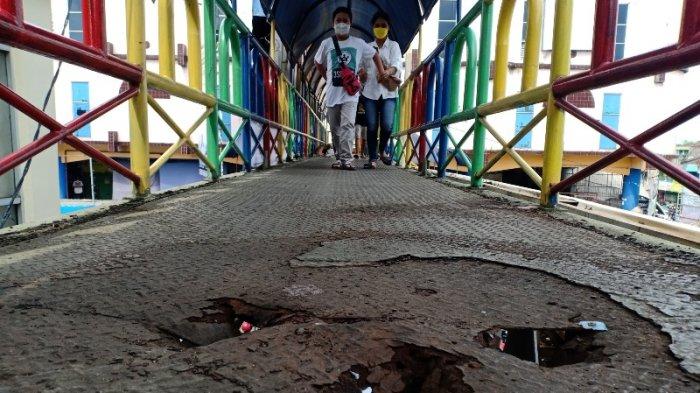JAKARTA - Pendidikan sering kali diidentikkan dengan ruang kelas, buku pelajaran, dan angka-angka pada lembar rapor. Namun dalam hiruk-pikuk dunia pendidikan yang semakin sibuk memenuhi target kurikulum dan capaian standar nasional, pertanyaan penting justru luput: masihkah pendidikan membuat kita merasa sebagai manusia?
Refleksi ini menjadi benang merah dari buku Pendidikan yang Membebaskan karya Pandu Wijaya Saputra. Di tengah tuntutan dunia kerja yang serba pragmatis dan sistem pendidikan yang kian terstandar, buku ini menawarkan sudut pandang segar bahwa esensi pendidikan bukan sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan menyentuh ranah terdalam manusia: rasa, budaya, dan makna.
Pendidikan sebagai Proses Kebudayaan
Alih-alih sekadar menyalahkan sistem, Pandu mengajak pembaca merenungkan ulang pendidikan dari kacamata budaya. Bukan budaya sebagai ornamen adat, melainkan sebagai cara manusia merespons dan memahami dunia. Menurutnya, pendidikan seharusnya menjadi jalan kebudayaan, bukan sistem yang membelenggu kreativitas.
Realitas di sekolah-sekolah menunjukkan bagaimana guru dan murid sering terperangkap dalam mekanisme administratif. Inovasi sering kali terhambat oleh kurikulum yang terlalu kaku. Guru yang ingin mengaitkan pelajaran matematika dengan konteks lokal, misalnya, akan menemui kesulitan karena sistem tidak mendukung metode kontekstual.
Di sisi lain, murid yang memiliki kecakapan non-akademik seperti bertani, memainkan alat musik tradisional, atau memahami siklus alam, justru dianggap "kurang cerdas" karena tidak unggul dalam ujian standar. Sistem pendidikan menilai berdasarkan seragamnya tolak ukur, bukan keberagaman potensi.
Sekolah Sebagai Laboratorium Budaya
Dalam buku ini, Pandu mengajukan konsep sekolah sebagai laboratorium budaya. Artinya, sekolah bukan hanya tempat menyerap informasi, tetapi juga ruang hidup untuk berinteraksi dengan realitas sosial dan alam sekitar. Bayangkan anak-anak belajar menenun dari pengrajin lokal, memahami pola tanam dari petani, atau membedah cerita rakyat sebagai bagian dari pelajaran bahasa dan sejarah.
Gagasan ini bukan romantisme masa lalu. Ini adalah bentuk nyata dari pendidikan yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari, yang menumbuhkan empati, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap lingkungan dan budaya lokal.
Sayangnya, pendidikan kita masih terlalu bergantung pada institusi formal. Orang tua sering kali menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada sekolah, sementara sekolah cukup puas dengan menyampaikan materi yang tercantum dalam silabus.
Padahal, seperti yang ditekankan dalam buku ini, pendidikan sejati justru terjadi dalam keseharian: dalam obrolan keluarga, dalam kerja sama komunitas, dalam cara kita memperlakukan orang lain dan menyikapi persoalan hidup.
Diskriminasi yang Masih Mengakar
Salah satu bagian paling menyentuh dalam buku ini adalah saat Pandu mengangkat kisah Ekalaya dari epos Mahabharata seorang murid berbakat yang ditolak oleh gurunya karena berasal dari kasta bawah. Cerita ini digunakan sebagai metafora untuk menunjukkan bahwa diskriminasi dalam pendidikan masih nyata: entah dalam bentuk kesenjangan akses, mahalnya biaya pendidikan, atau bias terhadap anak-anak dari daerah terpencil.
Pendidikan yang membebaskan, dalam hal ini, bukan hanya soal metodologi, tetapi juga tentang keadilan: siapa yang boleh belajar, siapa yang bisa mengakses kualitas, dan siapa yang tersisih oleh sistem.
Literasi: Lebih dari Sekadar Membaca
Pandu juga memberi perhatian besar pada krisis literasi. Ironisnya, di era teknologi informasi, kemampuan membaca anak-anak justru menurun. Bukan hanya membaca secara teknis, tetapi membaca dalam arti niteni mengamati, mengolah, dan memaknai informasi secara kritis.
Ia menyoroti bagaimana sistem pendidikan lebih banyak menekankan hafalan daripada pemahaman, menilai kemampuan dari angka, bukan dari cara berpikir atau keberanian bertanya.
Literasi sejati, menurut Pandu, adalah ketika anak-anak mampu membaca dunia, bukan hanya membaca teks. Dalam konteks ini, guru dan orang tua memegang peran sentral: bukan sekadar penyampai informasi, tetapi fasilitator proses tumbuhnya akal dan rasa.
Seni, Sastra, dan Pendidikan Emosi
Aspek lain yang tak kalah penting adalah pentingnya pendidikan seni dan sastra. Di tengah dunia yang makin bising dan tergesa, pelajaran seperti musik, puisi, atau teater sering kali hanya dianggap pelengkap. Padahal, dari situlah anak-anak belajar memahami emosi, menyuarakan isi hati, dan merasakan pengalaman orang lain semua elemen penting dalam membentuk manusia yang utuh.
Sayangnya, dalam sistem yang terlalu teknokratis, kemampuan ini sering dianggap tak berguna. Padahal justru lewat seni, anak belajar menjadi manusia yang empatik dan beradab.
Ruang untuk Tumbuh, Bukan Sekadar Lulus
Buku Pendidikan yang Membebaskan tidak hadir sebagai teori kaku atau nostalgia masa lalu. Ia ditulis dalam bentuk esai, reflektif dan mengalir seperti percakapan. Meskipun formatnya membuat beberapa gagasan terasa belum tuntas, justru pendekatan ini menjadikan buku terasa hidup, seperti ajakan berdialog, bukan dakwah sepihak.
Pandu menyadarkan kita bahwa membicarakan pendidikan berarti juga bicara tentang masa depan bangsa. Maka, untuk menindaklanjuti gagasan ini, dibutuhkan langkah konkret: sekolah-sekolah yang berbasis budaya lokal, kurikulum yang memberi ruang fleksibel, pelatihan guru yang menyentuh aspek filosofis, dan kebijakan yang mendengar suara dari bawah.
Sebab pendidikan yang membebaskan bukanlah utopia. Ia mungkin dan perlu diperjuangkan. Dimulai dari hal-hal sederhana: melihat anak bukan sebagai angka di rapor, tetapi sebagai manusia yang sedang belajar merasa, berpikir, dan bertumbuh.