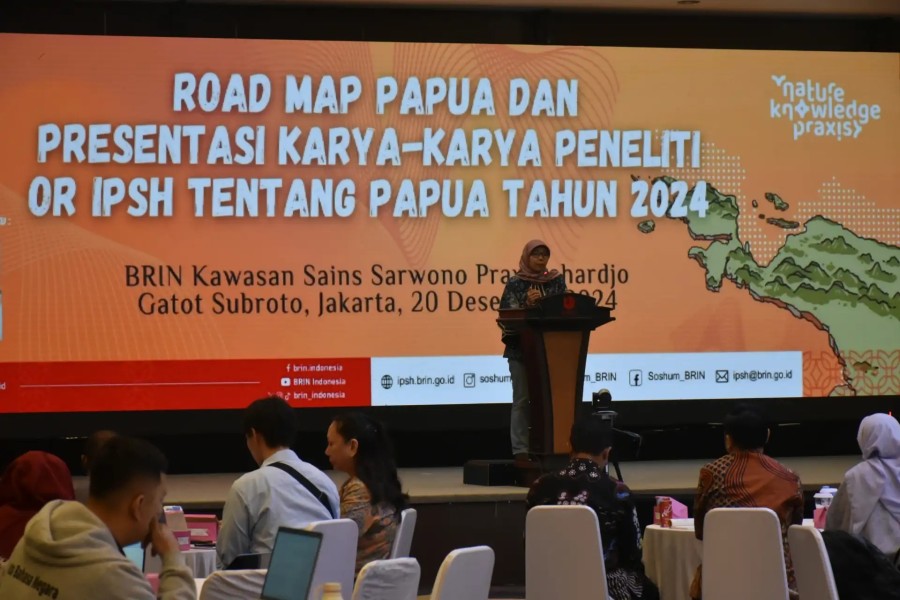JAKARTA - Di balik klaim kemajuan transisi energi dan janji dunia yang lebih bersih, sebuah tragedi ekologi tengah berlangsung di Halmahera, Maluku Utara. Aktivitas pertambangan nikel yang masif—terutama di kawasan Teluk Weda dan sekitarnya—telah mengubah surga alam menjadi zona bencana lingkungan. Hutan gundul, sungai tercemar, laut tercemar logam berat, dan masyarakat pesisir terhimpit krisis air bersih.
Teluk Weda: Dari Surga Laut Menjadi Kawasan Industri
Dulu, Teluk Weda adalah jantung segitiga terumbu karang dunia, dipenuhi koloni karang besar dan rumah bagi ragam hayati laut. Di dasar lautnya, hiu berjalan (Hemiscyllium halmahera), spesies endemik, merayap pelan dalam gelap, tak terburu-buru. Namun, sejak dimulainya proyek Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), kawasan ini berubah drastis. Pembangunan smelter nikel dan infrastruktur industri lainnya telah mengubah lanskap ekologis Teluk Weda secara permanen.
Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem
Aktivitas pertambangan nikel di Halmahera telah menyebabkan deforestasi besar-besaran. Data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa sejak 2001 hingga 2022, Kabupaten Halmahera Tengah kehilangan 26.1 ribu hektare tutupan pohon, Halmahera Timur kehilangan 56.3 ribu hektare, dan Halmahera Selatan kehilangan 79.0 ribu hektare. Kehilangan hutan ini setara dengan emisi karbon dioksida yang sangat besar, memperburuk krisis iklim global.
Selain itu, kegiatan pertambangan juga merusak Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan risiko bencana banjir bandang. Sejak 2020, wilayah sekitar IWIP telah mengalami tujuh kali bencana banjir bandang, yang diduga akibat kerusakan DAS oleh aktivitas industri nikel. Limbah tambang juga mencemari perairan, mengancam kehidupan biota laut dan merusak habitat ikan.
Pencemaran Laut dan Krisis Perikanan
Nelayan di Teluk Weda kini menghadapi krisis. Sebelum adanya aktivitas tambang, mereka dapat menangkap 10 hingga 50 kilogram ikan per hari. Namun, pada 2024, hasil tangkapan menurun drastis menjadi hanya 6 kilogram per hari. Pencemaran logam berat seperti krom heksavalen, nikel, dan tembaga di perairan telah melebihi ambang batas baku mutu, mengancam kesehatan manusia dan kelangsungan hidup spesies akuatik.
Seorang nelayan, Hernemus Takuling, mengungkapkan bahwa pipa dari pabrik peleburan IWIP membuang limbah ke laut, mengubah air laut menjadi cokelat kekuningan. “Biasanya, saya harus berperahu hingga 4 kilometer dari ujung pantai, kondisi ikan yang ditangkap di sana jauh lebih baik,” katanya.
Krisis Air Bersih dan Dampaknya pada Masyarakat
Kehidupan masyarakat pesisir semakin terhimpit akibat krisis air bersih. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber utama air bersih kini tercemar dan tidak dapat digunakan lagi. Marcelina Kokeno, warga Desa Gemaf, mengatakan, “Dulu sebelum ada tambang, sungai itu kami jadikan sebagai sumber utama air bersih, dan bisa menangkap ikan, udang, bia kole (kerang), namun saat ini, sudah tidak bisa, sungainya tidak pernah jernih lagi.”
Selain itu, polusi udara dari pembangkit batu bara yang menyuplai listrik ke kawasan industri juga mencemari udara Maluku Utara. Di Desa Lelilef, tempat IWIP beroperasi, angka kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA) mengalami peningkatan konsisten.
Kecelakaan Kerja dan Dampak Sosial
Praktik industri yang serampangan telah berujung pada rangkaian kecelakaan kerja. Sejak dimulainya masa operasional PT IWIP pada 2018, telah terjadi empat kali kecelakaan ledakan dan sekali kebakaran dengan puluhan korban buruh. Ledakan smelter IWIP akhir 2023 lalu menambah korban, mengakibatkan 25 korban jiwa dan puluhan korban luka bakar.
Muhammad Aris, seorang akademisi dari Ternate, menuturkan, “Pemerintah banyak mengklaim soal dampak positif ekonomi dari hilirisasi nikel, namun kalau diukur, dampak ekonomi dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan sangat masif dan sulit diukur.”
Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kehidupan Masyarakat
Kerusakan habitat alami di Weda, Halmahera, telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap keberlangsungan ekologi lokal, khususnya bagi flora dan fauna endemik. Lebih dari 20% dari habitat asli di wilayah terdegradasi dalam dekade terakhir akibat aktivitas ekstraksi dan industrialisasi. Spesies endemik seperti Burung Madu Halmahera kini terdaftar dalam kategori rentan oleh IUCN Red List, dengan populasi yang terus menurun karena hilangnya habitat.
Degradasi lingkungan ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hasil alam kini menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial. Mereka harus melaut lebih jauh dengan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan ikan, dan harus membeli air bersih yang sebelumnya dapat diperoleh secara gratis.